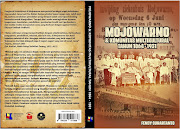Han Sing Tjiang Tahun 1940-an
(Sumber: Basuki Soejatmiko, 1982: 286)
Sejarah tidak hanya membincangkan tentang dikotomi penjajah vs terjajah, bangsa asing vs pribumi, atau bahkan nasionalisme vs imperialisme. Salah satu kelemahan historiografi indonesiasentris pada akhirnya menempatkan masa lalu secara dikotomis. Karenanya, historiografi alternatif cukup menarik perhatian dewasa ini. Seperti yang diulas Bambang Purwanto dalam bukunya berjudul Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!.
Dinamika sejarah tentu sangatlah cair. Begitu banyak warna, bukan sekedar hitam dan putih. Tapi tak dapat dipungkiri juga terkadang cukup rumit, apalagi di era post truth. Ketika hyper information telah menjadi bagian zaman. Maka kerumunan opini bisa mematikan fakta, bahkan kebenaran itu sendiri.
Termasuk kisah tentang orang-orang Tionghoa di Mojokerto. Ada banyak fakta yang cukup unik dan menarik. Salah satunya dari sosok bernama Han Sing Tjiang. Lulusan Europ. Lagere School Djombang, seperti yang tertulis pada suntingan buku oleh Basuki Soejatmiko berjudul Etnis Tionghoa di Awal Kemerdekaan Indonesia sorotan Bok Tok Pers Melayu-Tionghoa Desember 1945-September 1946 (1982: 286).
Pada tahun 1928, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan bestuurshervorming, atau penataan pemerintahan. Kebijakan tersebut dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1928 No. 464. Konsekuensi adanya kebijakan tersebut maka dibentuk Regentschapsraad Modjokerto, atau Dewan Kabupaten Mojokerto.
Surat kabar Soerabaijasch Handelsblad, 29 Januari 1929 memuat berita tentang rencana pelantikan anggota Regentschapsraad Modjokerto. Rencananya dilantik pada Rabu 6 Februari 1929 pukul 9 pagi. Bertempat di Societeit Concordia oleh C. A. Schnitzler, selaku Residen Mojokerto. Dewan Kabupaten Mojokerto berjumlah 19 orang. Terdiri dari 13 penduduk pribumi, 4 orang Eropa, 1 orang Arab, dan 1 orang Tionghoa.
Susunan dewan tersebut merupakan yang pertama kali di Mojokerto. Untuk perwakilan orang Tionghoa diisi oleh Han Sing Tjiang yang disebut koopman te Modjokerto, atau pedagang di Mojokerto tulis surat kabar Soerabaijasch Handelsblad, 29 Januari 1929.
Nama-Nama Anggota Regentschapsraad Mojokerto Tahun 1930-an
(Sumber: Voornaamste Voorschriften en Personalia betreffende de Decentralisatie en de Bestuurshervorming, alsmede de Grondwet en de Indische Staatsregeling, 1931: 238)
Profil Han Sing Tjiang selain sebagai anggota Dewan Kabupaten Mojokerto dan pedagang, juga merupakan pegawai pabrik gula di Mojokerto. Yang juga lulusan Suiker School, yakni sekolah yang mendidik calon tenaga kerja pada industri gula. Pada awal abad ke-20, sekolah tersebut ada di Surabaya dan Madura.
Selepas dari Suiker School, Han Sing Tjiang bekerja di SF Sentanan Lor sebagai Chemiker. Pindah ke SF Pohjejer sebagai docter kebon. Kemudian pindah ke SF Tangunan menjabat sebagai Fabriekatie-chef (Basuki Soejatmiko, 1982: 286). Jabatan Chemiker ialah sebutan untuk kepala bagian penggilingan di pabrik gula. Jabatan docter kebon ialah kepala kebun, dan Fabriekatie-chef yang dapat diartikan sebagai manajer atau kepala produksi di pabrik gula.