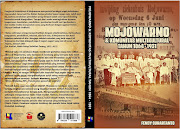Relief kapal pada panel candi Borobudur sekitar abad ke-9 M
(dok: Repro A.B. Lapian, 2008)
Pemanfaatan sungai dan laut sebagai jalur pelayaran tidak hanya sekedar hipotesis belaka. Ada banyak data sejarah yang mendukung teori tersebut. Bukti otentik terkait pelayaran terdapat pada relief kapal atau perahu pada panel relief candi Borobudur. Artinya, sejak masa Mataram Kuno Jawa Tengah, antara abad ke-7 sampai ke-9 Masehi masyarakat Jawa telah mengenal pelayaran. Termasuk, cara bagaimana mereka membuat kapal atau perahu.
Di Pulau Jawa banyak sekali bahan baku pembuatan kapal atau perahu. Kayu jati (Tectona Grandis) merupakan bahan baku utama pembuatan kapal atau perahu di Jawa. Selain jumlahnya banyak, kayu jati mempunyai keunggulan, terkait aspek kekuatan kayunya. Kapal atau perahu dari kayu jati tampaknya dapat tahan lama. Maka dari itu, di pesisir utara Jawa terdapat tempat-tempat pembuatan dan perbaikan kapal. Industri pembuatan dan perbaikan kapal sudah ada sejak masa Jawa kuno.
Data prasasti juga menyebutkan aktivitas penggunaan kapal atau perahu. Baik yang memanfaatkan sarana sungai maupun laut, yaitu; prasasti Gulung-Gulung (929 M), prasasti Saranan (929 M), prasasti Linggasuntan (929 M), prasasti Turryan (929 M), prasasti Jeru-Jeru (929 M), prasasti Candi Lor (935 M), prasasti Wimalasrama (masa Mpu Sindok), prasasti Cane (1021 M), prasasti Baru (1030 M), prasasti Turunhyan A (1035 M), prasasti Kamalagyan (1037 M), prasasti Gandhakuti (1042 M), prasasti Patakan (masa Airlangga), prasasti Mananjung (diperkirakan abad ke-11 M), prasasti Kambang Putih (1093 M), prasasti Hantang (1135 M), prasasti Jarin (1181 M), prasasti Balawi (1305 M), prasasti Tuhanaru (1323 M), prasasti Canggu (1358 M), dan prasasti Waringin Pitu (1447 M). Seperti yang ditulis oleh Hedwi Prihatmoko (2011), dalam skripsinya berjudul Pengelolaan Transportasi Air Abad X Sampai XV Masehi di Jawa Timur Berdasarkan Sumber Prasasti (hlm. 40-64).
Dalam penelitian J. W. Christie (1982: 515-521) berjudul Patterns of Trade in Western Indonesia: Ninth Through Thirtheenth Centuries A.D (Vol. I & II), yang menterjemahkan prasasti Wimalasrama menyebutkan:
“maramwan tlung ramẃan, parahu 6, masunghᾱra 6 kunang ikang hiliran, akiran agöng 6, akirin tᾱ 8, mbᾱtᾱmbᾱ 6, amayang 6 amukét kakap 6 amukét arp 6, atadah 6 anglamboan 6, amaring..”
Artinya: pedagang yang menggunakan rakit/perahu kayuh (batasnya) 3 pedagang, perahu (batasnya) 6, perahu sungai (dengan tiang?) (batasnya) 6, pedagang hilir sungai (batasnya) 6, perahu pengangkut barang-barang besar (batasnya) 6, perahu pengangkut obat-obatan (batasnya) 8, nelayan dengan pukat paying (batasnya) 6, nelayan kakap (batasnya) 6, nelayan kerapu (batasnya) 6, atadah (batasnya) 6, nelayan dengan perahu lambo (batasnya) 6, amaring.
Nama-nama perahu berdasarkan bentuknya
(Repro, Hedwi Prihatmoko, 2011: 85)
Pentingnya Sarana PenyeberanganSelain nama-nama perahu, uraian pada prasasti juga menyebutkan suasana hati para nahkoda dan pedagang. Ditulis oleh Ninie Susanti (2003) dalam penelitiannya berjudul Airlangga: Raja Pembaharu di Jawa Pada Abad Ke-11 M (hlm. 423). Seperti yang terpahat pada prasasti Kamalagyan (1037 M), berikut penggalan kalimatnya:
“..rikᾱn para puhᾱwan para banyaga sańkᾱriŋ dwīpᾱntara sama ńunten ri hujuŋ galuh ikań anak thᾱni Śakawᾱhan kadédétan sawahnya atyanta sarwwasukha ni manahnya makᾱnta ta sawaha muwah sawahnya kabeh an pinunyan”.
Artinya: demikian para nahkoda (puhawan) dan pedagang dari pulau lain bertemu di Hujung Galuh. Penduduk yang tanah pertaniannya terkena banjir sangat senang hatinya karena berakhirlah banjir itu dan dengan ini seluruh hasil sawahnya dapat dimiliki.
Informasi tersebut memperlihatkan pentingnya pelayaran di Sungai Brantas. Para pedagang pun menyusuri lembah Sungai Brantas (bisa juga di Sungai Bengawan Solo) untuk mendatangi pusat-pusat ekonomi di pedalaman Jawa. Tentu ada perbedaan terkait penggunaan jenis kapal. Berbeda dengan pelayaran di laut yang membutuhkan kapal-kapal berukuran besar. Pelayaran di Sungai Brantas dan Bengawan Solo tentunya menggunakan kapal-kapal yang ukurannya relatif kecil. Kapal ukuran kecil atau perahu dapat bermanuver di aliran sungai yang dangkal dan tidak terlalu lebar.
Pada uraian prasasti terdapat beberapa istilah yang terkait dengan alat transportasi air, seperti; parahu, sunghar, tundan, galah, ramwan, langkapan, wlah, banawa, panggagaran, joron, kétpak, lambu, kuńjalan, amayang, dan lancang. Seperti yang ditulis oleh Adrian B. Lapian (2008) dalam bukunya berjudul Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17 (hlm. 49-50).
Nama-nama kapal atau perahu tersebut yang digunakan di Jawa (terutama Jawa Timur) saat itu. Jenisnya beranekaragam dan tentu disesuaikan untuk penggunaannya. Ada yang untuk transportasi di sungai dan ada juga untuk transportasi di laut. Ada yang digunakan mengangkut barang, mencari ikan, dan penyeberangan di sungai.
Penyeberangan di sungai banyak diuraikan dalam prasasti. Daerah-daerah penyeberangan, baik di Sungai Bengawan Solo dan Brantas jumlahnya sangat banyak. Para penguasa Jawa kuno telah memperhatikan pentingnya tempat-tempat penyeberangan.
Dalam penelitian Ninie Susanti (2007), berjudul Pengelolaan Transportasi Pada Masa Jawa Kuno Abad VIII-XV: Kajian Arkeologi disebutkan pertama kali tercatat pada prasasti Telang (893 M) terkait dengan pembuatan tempat penyeberangan di Paparahuan (pinggiran Sungai Bengawan Solo) dan penjagaannya, sehingga Desa Telang-Mahe-Paparahuan dijadikan Sima (hlm. 14). Pada masa berikutnya, perhatian terhadap tempat-tempat penyeberangan semakin meningkat.
Puncaknya pada masa imperium Majapahit, dengan dikeluarkannya sebuah prasasti oleh Raja Hayam Wuruk. Prasasti yang ditemukan di Canggu, wilayah utara Mojokerto. Prasasti Canggu (1358 M) berisi nama-nama tempat penyeberangan di seluruh Jawa, yang menjadi wilayah inti Majapahit. Raja memerintahkan tempat-tempat tersebut untuk dijaga atau dirawat. Adapun petugas penyeberangan saat itu yang disebut dengan “anambangi”.
Penyeberangan Sungai Brantas di Megaluh Jombang Sekitar Tahun 2019
(Sumber: https://radarjombang.jawapos.com/nasional/66989925)