Ganas, memang sangat ganas wabah Covid 2019. Melumpuhkan negara sekalipun. Sepanjang bulan Januari sampai Mei tahun 2021, sudah membuat defisit APBN lebih dari 200 trilyun. Negara megap-megap, apalagi rakyat. Yang sebagian besar bukan penikmat langsung APBN.
Situasi tak menentu dan negara abstain. Aparat sebagai pejabat publik sibuk menyelamatkan diri. Hingga menyelamatkan karirnya tanpa malu. Koruptor berpesta pora. Sebab wabah menghambat penegakan hukum. KPK yang independen, menjadi tidak merdeka. Pegawainya telah menjadi ASN, yang pada prinsipnya harus hormat pada atasan. SIAP NDAN! Tak peduli atasannya salah sekalipun.
Tapi ini bukan soal Covid, atau bahkan KPK. Tapi soal pertanda. Tentang wabah tikus di pedesaan. Menyerang tanaman petani. Orang-orang Jawa dulu suka menghubung-hubungkan. Keadaan di sekitar mereka, dengan kondisi yang sedang dan akan dialami kerajaan. Wabah tikus adalah pertanda. Negara dalam keadaan bahaya.
Tikus Menyerang Tanaman Jagung
(Sumber: http://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/3299/)
Wabah Tikus dalam Tradisi Jawa
Beda masyarakat, beda kebiasaan. Bagi masyarakat Manado, tikus menjadi menu santapan. Di Pasar Tomohon, daging tikus dijual. Dijajakan di lapak-lapak pedagang. Mereka sudah terbiasa menyantapnya. Konon, hanya tikus hutan yang jadi hidangan.
Masyarakat Jawa dan sebagian lainnya, tidak terbiasa. Dalam tradisi Jawa, tikus adalah mahkluk yang kotor. Tidak layak di konsumsi. Pada tahun 1910-1916, di Malang pernah terjadi wabah pes. Penyakit yang dibawa oleh tikus. Saat ini pun tikus jadi musuh petani. Dalam semalam saja, gerombolan tikus mampu menghabiskan tanaman pak tani. Jadi, yang suka mencuri bukan lagi kancil, tapi tikus. Kancil sekarang hewan yang sulit ditemukan di Jawa.
Onghokham, pada bulan Desember 1965 berkunjung ke Jawa Timur. Sejarawan nyentrik spesialis Jawa ini, memang berasal dari Pasuruan. Meski Orang Tionghoa, ia sangat menyukai budaya Jawa.
Dikutip dari David Reeve (2018), pada epilog buku Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX, Onghokham menyaksikan wabah tikus di pedesaan Jawa. Ia prihatin atas gejolak di pedesaan Jawa, dan keadaan ekonomi yang tak terkendali (hlm. 340).
Wabah tikus menyengsarakan petani. Membuatnya gagal panen. Kelangkaan bahan pangan merajalela. Kalaupun ada, kantong penduduk pedesaan tak cukup membelinya. Musim paceklik pun terjadi. Kalau paceklik tahun 1965-an, diikuti bencana pembunuhan massal. Paceklik tahun 2020-an, diselingi pagebluk Covid 2019.
Pagebluk dan wabah tikus menjadi pertanda. Sedang atau akan terjadi gonjang-ganjing politik. Negara salah urus, negara gagal, rakyat jadi tumbal. Semua itu diawali penderitaan rakyat kecil. Jadi korban salah urus negara. Akibat penguasa dan pembesar sibuk urus diri sendiri. Rakyat kecil harus menanggungnya.
Sejak dahulu kala, pertanda zaman dibaca pujangga. Dari Jayabaya hingga Ronggowarsito. Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowarsito (1802-1873). Menulis kegelisahan itu dalam Serat Kalatidha (1860). Menggambarkan tanda datangnya zaman kekacauan atau zaman edan, tulis David Reeve (2018: 340).
Ronggowarsito melihat dengan kepala sendiri. Saat terjadi Perang Jawa (1825-1830). Juga mengalami langsung Cultuur Stelsel (1830-1870). Ia menyaksikan carut marut kehidupan masyarakat Jawa. Konflik antar pembesar, dan konflik antara Diponegoro dengan Belanda. Rakyat pedesaan menjadi korban perang. Lanjut korban kebijakan tanam paksa.
Meruwat Pagebluk dan Wabah Tikus
Tiap-tiap manusia sejatinya seorang negosiator. Bahkan dalam alam tak nyata sekalipun. Tradisi ruwatan juga selalu dikaitkan dengan alam tak nyata. Di luar nalar dan logika.
Ketika muncul kekacauan, akibat pagebluk dan wabah tikus, yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sains. Akan mencari jalan supranatural. Orang Jawa biasanya melakukan ruwatan. Untuk mengembalikan keadaan sebelum kekacauan. Menyeimbangkan makrokosmos, dunia di luar diri manusia.
Dalam tradisi Bali, pernah memiliki kaitan erat dengan peradaban Jawa kuno. Mengenal Caru atau Mecaru. Menurut Pinandita I Ketut Pasek Swastika, Caru untuk menjaga keseimbangan jagat raya. Sebagai pembersih dan penyucian kembali dari pengaruh kotor. Sarananya memberikan beragam hidangan. Berupa nasi, tumbuhan, binatang, dan unsur-unsur alam lainnya (2011: 11-12).
Jagat raya yang tidak harmonis, bisa karena beragam hal. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bencana alam. Wabah tikus pertanda jagat raya kurang harmonis. Hewan pengerat memakan tanaman petani. Rakus, dengan sangat rakus sekali.
Segala cara telah dilakukan petani. Memasang setrum (aliran listrik), jaring, hingga memberi racun. Tak jarang petani menggropyok tikus bersama-sama. Cara logis ini pun masih belum mampu menyelesaikan soal tikus.
Di tengah suasana frustasi, petani memakai cara klenik. Memberi sesajen. Menyiram dengan air yang diambil dari tujuh sumber mata air (sumur). Menurut Isharyanto, Juru Pelihara Candi atau Patirtaan Tikus di Trowulan, terkadang penduduk sekitar mengambil air. Digunakan untuk melindungi tanaman padi dari serangan tikus.
Saat ini, tikus mengancam eksistensi petani. Membuatnya gulung tikar. Persis koruptor yang menilap APBN. Dua-duanya menjadi mahkluk yang kotor. Tetapi, di zaman edan ini, keduanya menikmati. Tanpa ada malu. Seperti yang pernah dituliskan Ronggowarsito.
Sejarah sebenarnya telah mengingatkan. Saking seringnya, barangkali menjadi lupa. Atau mungkin saja abai (pura-pura lupa). Kehancuran kerajaan-kerajaan zaman Hindu-Budha, Islam, dan VOC akibat salah urus. Pengurus mengutamakan korupsi dan sewenang-wenang. Padahal, pengurus harus mengabdi pada rakyat. Mestinya, dalam birokrasi modern, pejabat dan aparat adalah pelayan publik.


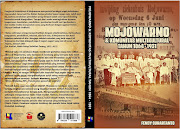




Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar Anda. Untuk perbaikan media pembelajaran sejarah populer ini.